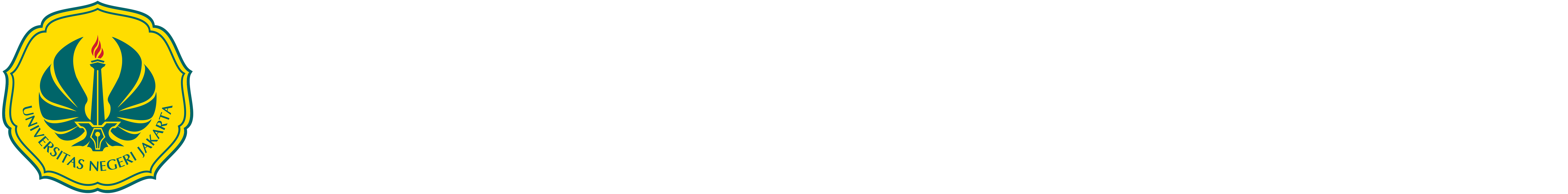Pendidikan karakter tidak bisa dimulai dari bangku kuliah atau sekolah menengah. Namun harus ditanamkan sejak dini, bahkan sejak anak berada di daycare. Demikian ditegaskan Prof. Ciek Julyati Hisyam, Guru Besar Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta (FISH UNJ), dalam paparannya di hadapan peserta kegiatan edukatif di salah satu pesantren di Indramayu pada 1 Mei 2025 lalu.
“Pendidikan itu dimulai dari keluarga,” ujarnya. “Karena keluarga adalah pembentuk norma pertama dalam masyarakat. Rumah adalah sekolah pertama, dan orang tua adalah guru pertama.”
Menurutnya, karakter anak tidak dibentuk oleh angka atau teori, melainkan oleh keteladanan nyata yang hadir dalam keseharian—baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Namun, Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis keteladanan yang serius.
Prof. Ciek menyoroti lemahnya figur panutan di ruang publik. Sebagai ahli Sosiologi Perilaku Menyimpang dan Pendidikan Karakter, Prof. Ciek menegaskan bahwa keteladanan bukan sekadar etika personal, melainkan fondasi moral bangsa. Jika keluarga gagal membentuk karakter dan publik kehilangan teladan, maka pendidikan nasional kehilangan pijakan.
Prof. Ciek menyambut baik keberadaan fasilitas daycare yang terintegrasi dengan sistem pendidikan karakter di pesantren. Ia menilai hal ini sebagai langkah strategis dalam membangun bangsa sejak usia dini.
“Pendidikan karakter di tingkat mahasiswa itu sudah terlambat. Harusnya dimulai dari PAUD atau daycare,” tegasnya. Ia bahkan mengusulkan agar tenaga pendidik PAUD memiliki latar belakang akademik yang kuat, minimal sarjana atau magister, agar mampu memahami dan menerapkan pendidikan karakter secara menyeluruh.
Pendidikan Karakter: Sinergi Rumah, Sekolah, dan Masyarakat
Prof. Ciek mengkritik sistem pendidikan nasional yang berjalan sendiri-sendiri. “Sekolah jalan sendiri, keluarga jalan sendiri, masyarakat jalan sendiri,” ujarnya. Padahal, ketiganya harus bersinergi dalam membentuk karakter anak.
Ia membagikan pengalaman pribadinya dalam menanamkan nilai kedisiplinan keuangan sejak anak usia sekolah dasar, seperti membiasakan membuat laporan keuangan harian dari uang saku bulanan. “Kalau akhir bulan saya tanya: kamu beli apa? Kalau nggak ada kuitansi, nggak ada rembes,” katanya.
Ia mengutip teori Thomas Lickona yang menyebut pendidikan karakter harus mencakup tiga dimensi, yaitu: pengetahuan moral (moral knowing), empati moral (moral feeling), dan tindakan moral (moral action).
Prof. Ciek Julyati Hisyam tidak hanya menyoroti pentingnya norma dan keteladanan dalam pendidikan karakter, tetapi juga mengangkat isu serius lain, yakni pelabelan sosial (labeling) yang merusak.
“Label itu diberikan oleh orang lain. Anak malas, dasar penjahat — itu bukan label yang dibuat sendiri,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa teori labeling dalam sosiologi menunjukkan bagaimana cap negatif yang dilekatkan oleh masyarakat dapat menghancurkan karakter seseorang, bahkan merusak citra sebuah institusi. Menurutnya, satu-satunya cara untuk mengubah persepsi publik adalah dengan menunjukkan karya nyata dan memperluas komunikasi.
Dalam penutupnya, Prof. Ciek menyampaikan harapan agar pendidikan di Indonesia menempatkan pembentukan karakter sebagai prioritas utama. Ia mengajak sekolah-sekolah lain untuk belajar dari pendekatan holistik yang diterapkan di pesantren-pesantren dan tentunya sangat penting dibarengi dengan keteladan.
“Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,” ujarnya, mengutip lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya. “Kalau kita sibuk mengurusi label negatif, kita tidak akan sempat membangun. Kita harus terus maju.”